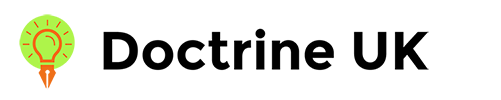Foto: Pemahkotaan Raja Charles III
Sumber: BBC
ARTICLE
Pemahkotaan Raja Charles III (Sabtu, 6/5/2023) merupakan peristiwa sejarah langka dan monumental. Mayoritas warga Inggris dan dunia belum pernah menyaksikan karena suksesi monarki serupa terjadi 70 tahun yang lalu saat penobatan Ratu Elizabeth II tahun 1953. Lantas apa signifikansi koronasi ini?
Menilik sejarah Inggris, pemahkotaan adalah bentuk seremoni penasbihan naik tahtanya penguasa baru. Raja perlu dimahkotai secara publik guna menciptakan stabilitas dalam masyarakat, terutama jika ada potensi gejolak dan kekuatan saingan yang mengklaim singasana.
Prosesi berisi “pengurapan” Raja dengan minyak suci untuk memberikan unsur sakral dan spiritual, serta pengharapan anugerah rahmat Ilahi. Mengikuti tradisi panjang, ritual dipimpin Uskup Agung Canterbury di Biara Westminster, yang juga berarti penghayatan konstitusi Inggris yang berintikan konvensi tidak tertulis.
Raja Tetap Berkuasa
Semenjak Magna Carta (1215) dan kemudian Bill of Rights (1689), kekuasaan mutlak raja dibatasi dan semakin menurun seturut dekolonialisasi dan keruntuhan imperium. Sistem politik Inggris—yang disebut sebagai monarki konstitusional—mengatur agar monarki berbagi kekuasaan dengan kepala pemerintahan yang dipegang perdana menteri pilihan rakyat. Sekalipun demikian, salah besar kalau mengira Raja beserta keluarga sudah tidak berkuasa secara signifikan.
Tidak lagi berkuasa absolut, tapi Raja tetaplah raja. Sebagai kepala negara, Raja berwenang membubarkan pemerintahan menjelang pemilihan umum dan merestui pembentukan pemerintahan baru. Raja mengesahkan undang-undang, menerima duta besar, menjadi panglima angkatan bersenjata, dan memimpin Gereja Inggris.
Mewarisi kebesaran imperium Britania Raya, Raja Inggris juga mengepalai 14 negara lain di seluruh dunia, seperti Australia, Kanada, Jamaika, dan Selandia Baru, dan memimpin Alam Persemakmuran, yaitu kelompok negara-negara bekas jajahan dan dependensi Inggris.
Kebanyakan publik memahami Raja hanya sebagai kepala negara simbolik dan pemimpin seremonial tanpa peranan eksekutorial. Padahal, Raja lazim bertemu Perdana Menteri saban Rabu di Istana Buckingham dan kerap menggelar rapat reguler dengan para pejabat senior dari berbagai instansi.
Dengan kuasa dan peran pemerintahan demikian, Raja membina hubungan dengan percaturan politik Westminster yang dinamis dan tidak stabil. Buktinya, baru saja mewarisi tahta September lalu, Charles sudah bermitra dengan dua perdana menteri. Liz Truss hanya bertahan selama 45 hari, dan sekarang Rishi Sunak juga berada di bawah bayang-bayang pemilu.
Sebagai sesama penguasa baru, Charles dan Sunak berbagi tantangan. Harmonisasi pengaruh Buckingham dan kekuasaan eksekutif/legislatif Westminster diperlukan untuk memperbaiki nasib rakyat yang menghadapi himpitan krisis biaya hidup, energi, inflasi dan kekurangan tenaga kerja, seturut Brexit dan pemulihan pasca pendemi.
Di level global, Raja ikut bertugas menjaga pengaruh Inggris Raya sebagai mantan penguasa dunia. Apalagi ikatan Persemakmuran dan hubungan khusus Anglo-American telah membentuk sejarah dunia dalam dua abad terakhir. Dalam urusan Persemakmuran, kepemimpinan Charles kritikal mengingat beredarnya keraguan dan wacana skema ketua bergilir.
Beruntungnya, Raja Charles sudah mulai menunjukkan kapasitasnya. Ia mendapat pujian setelah sukses melakoni misi diplomasi pertama, menjadi Monarki Inggris pertama yang berpidato di Parlemen Jerman (the Bundestag, Maret 2023).
Sektor Ekonomi Kerajaan
Tugas internasional Raja sekaligus mengemban peran memperkuat hubungan ekonomi dan dagang dengan dunia, termasuk tetangga Eropa yang memburuk akibat Brexit. Keluarga kerajaan memang diakui berkontribusi signifikan terhadap perekonomian. Bahkan, the Royal Family sendiri disebut sebagai sebuah firma (the firm), pelaku ekonomi sektor pariwisata dan pertunjukan. Seluruh aspek kehidupan keluarga kerajaan dikemas sebagai paket show biz, mulai dari kelahiran, ulang tahun, perkawinan, jubilee, hingga prosesi pemakaman. Pengemasan momen-momen spesial demikian sudah lama berlangsung dan diniatkan sebagai penggerak ekonomi.
Dalam prosesi panjang pemahkotaan Raja Charles III tempo hari, London disulap menjadi panggung pementasan yang megah. Di sepanjang jalan the Mall yang rindang antara Buckingham Palace dan Wesminster Abbey tersaji pertunjukan teater ruang terbuka, di bawah bidikan kamera dan liputan media seantero dunia. Raja sendiri bertindak sebagai aktor utama, didukung para pangeran dan putri, bala tentara, dan petugas, lengkap dengan pakaian dan ornamen kebesaran dalam pawai dan parade.
Layaknya konser penampil kelas dunia, pentas ini sudah dinantikan dan segera memicu efek domino pada perekonomian karena pesta dan kehebohan juga berlangsung di seluruh negeri. Tidak heran jika pengumuman resmi hari pemahkotaan saja sudah membuat tingkat hunian hotel melesat. Tren serupa diikuti oleh kenaikan peredaran restoran, pub, hiburan, dan produk-produk turunannya.
Kontribusi ekonomi kerajaan memang tidak main-main. Laporan dari Brand Finance (2017) memperkirakan aset Monarki Inggris bernilai £67,5 miliar atau sekitar Rp1.200 triliun, cukup kompetitif disandingkan dengan merek-merek korporat besar dunia. Konon the Royal Warrant, label yang mengaitkan bisnis dan produk dengan citra pelayanan, tradisi dan warisan Monarki, bisa membantu mendongkrak omset usaha.
Barangkali berkah ekonomi demikian turut melanggengkan institusi monarki dan bahkan mendapatkan dukungan. Survei oleh YouGov/BBC Panorama (2023) menunjukkan mayoritas warga lebih senang mempertahankan sistem monarki (58%) ketimbang kepala negara yang dipilih (26%). Rakyat pembayar pajak sepertinya tidak keberatan menanggung biaya hidup keluarga kerajaan yang ternyata tidak signifikan (£4.5 per kapita menurut Brand Finance).
Penyuplai Diskursus Identitas
Sejatinya Raja terikat relasi kontrak sosial saling membutuhkan dengan rakyat. Dalam politik praktis, Raja memang netral dan tidak memiliki hak pilih dan dipilih, namun tidak lantas berarti posisinya selalu aman. Gerak-gerik Raja akan senantiasa dipantau, terutama oleh kubu republikan yang ingin mengakhiri sejarah monarki. Ditambah lagi, media massa Inggris terkenal ‘kejam’ dan begitu pula kekuatan demokrasi digital di tangan warganet dan media sosial.
Raja perlu mengamankan dukungan rakyat karena legitimasinya ada pada kecintaan dan penerimaan rakyat. Tidak ada pemilihan umum untuk kontestasi politik keluarga kerajaan, tapi rakyat punya ‘suara.’ Seperti telah disebutkan, walau jajak pendapat tidak menentukan elektabilitas, hasilnya sanggup menyuarakan akseptabilitas yang mengindikasikan legitimasi.
Untuk merebut hati rakyat, Monarki Inggris tampak lihai mengoptimalkan posisi Raja sebagai Pimpinan Bangsa (Head of Nations) dengan menjadi fokus identitas, kesatuan, dan kebanggaan nasional. Raja dan keluarga melakoni ‘persona’ idaman yang menjadi kiblat refleksi identitas nasional, terutama dalam dinamika kehidupan modern global.
Seperti dikatakan Giddens (1991:5), di tengah ketidakpastian dan kecemasan yang dibawa arus modernitas, individu membutuhkan narasi ke mana refleksi identitas diri diarahkan. Keterbukaan kehidupan sosial belakangan semakin memaksa individu menegosiasikan pilihan gaya hidup di antara keragaman opsi. Institusi kerajaan tampil menyajikan diskursus gagasan gaya hidup sebagai sumber referensi bagi individu rakyat dalam melakukan (re)konstruksi narasi diri.
Sembari tetap menghormati demokrasi, Monarki mengambil strategi positioning yang menyasar ceruk urusan publik yang tidak tergarap oleh politisi dan pelaku bisnis. Keluarga kerajaan aktif merangkul komunitas, mempromosikan kegiatan amal, dan mendukung cita-cita pelayanan sukarela untuk golongan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Berbagai anugerah gelar dan pemberian penghargaan diamplifikasi untuk mengapresiasi kesuksesan dan keunggulan para pelayan publik, tentara, sekolah, rumah sakit, badan amal, dan organisasi lokal.
Aktivitas demikian bukan sekadar pencitraan, tapi justru melalui sifat simbolik dan seremonial inilah kekuasaan kini sebenarnya bekerja. Lakon inspirasi identitas nasional juga merangkap sebagai media yang memfasilitasi kekuasaan dalam mengendalikan perilaku rakyat yang mungkin lebih efektif dibanding menggunakan sovereign power secara memaksa. Dalam disiplin studi organisasi, misalnya, pengendalian melalui pengaturan identitas diyakini sangat efektif karena menyasar bagian dalam (the “inside”) individu (Alvesson & Willmott, 2002) yang membentuk siapa mereka dan menentukan perilaku kepatuhannya.
Sebagai figur penyatu, posisi netral Raja menjadikannya sokoguru negara yang lebih dipercaya dalam instabilitas sistem politik parlemen yang lekat dengan kepentingan kelompok dan partai. Monarki menghadirkan perasaan stabil, kepastian, dan kontinuitas, bahkan di saat krisis, bagi seluruh rakyat Inggris Raya sebagai suatu kerajaan bersatu. Raja berperan sebagai turus negara, sosok persona nasional yang menjadi perekat, sekaligus wasit yang adil bagi anak bangsa yang berkompetisi menawarkan ikhtiar terbaik melayani rakyat.
Dengan demikian, pemahkotaan dapat dibaca sebagai upacara kenegaraan pengokohan konstruksi kekuasaan konstitusional Monarki di bidang politik, ekonomi, dan sosial yang menyentuh relung hati rakyat. Raja Charles perlu dilantik untuk tampil karismatik dan dicintai mayoritas rakyat dan Sumpah Penobatan dilantangkan sebagai wujud komitmen melayani dan mencintai, memenuhi ekspektasi dan hasrat emosional rakyat. Untuk menarik dukungan (baca: legitimasi) lebih menyeluruh, takhta dan istana dihiasi megah sehingga mengundang rakyat bernostalgia, karena kejayaan Inggris, bagaimanapun, adalah warisan sejarah ketika Monarki sangat kuat. Harapannya, stabilitas negara terwujud dan rakyat yang hatinya takluk bahagia menyanyikan ‘God save the King’.
***
Keterangan:
Artikel ini merupakan aset pengetahuan organisasi dengan nomor registrasi DOCTRINE UK No. 2023-04-14-Articles. Doctrine UK tidak bertanggung jawab atas pandangan yang diungkapkan dalam tulisan dan pandangan tersebut menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.