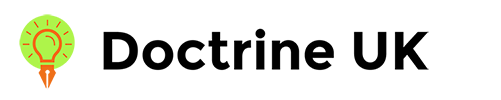Sumber: Identitas (pexels.com)
Articles
Penulis: Joseph Robert Daniel, Mahasiswa Doktoral bidang Manajemen di University of Liverpool.
Identitas merupakan salah satu konsep yang paling sering dibicarakan dalam ilmu sosial. Di bidang ilmu consumer research, konsep ini telah lama ditelaah menggunakan beragam pendekatan. Schau (2019), misalnya, menyebut bahwa penelitian tentang identitas dalam riset konsumen pada umumnya mengeksplorasi empat aspek: kepribadian (personality), konsep-diri (self-concept), proyek identitas (identity projects), dan presentasi-diri (self-presentation). Riset pada aspek yang pertama, kepribadian, biasanya dikerjakan oleh para sarjana yang lebih terbiasa dengan paradigma dan pendekatan ilmu psikologi. Kepribadian, diuraikan oleh Schau (2019), merujuk pada sekumpulan fitur yang membentuk karakter seorang individu, dianggap relatif stabil dan dikungkung oleh kecenderungan-kecenderungan yang sifatnya genetik [1].
Para sarjana lain yang menggunakan pendekatan sosiologis, umumnya, lebih tertarik untuk meneliti ketiga aspek yang lain, yakni konsep diri (bagaimana seseorang memahami siapa dirinya), proyek identitas (bagaimana seseorang menggunakan beragam sumber daya kultural: objek, simbol, praktik sosial, mitos, dan sebagainya, untuk menjaga, mengembangkan, atau mentransformasi pemahaman tentang dirinya), dan presentasi-diri (bagaimana individu menunjukkan identitas mereka, atau pemahaman diri mereka, dalam suatu konteks sosial).
Makalah sederhana ini disiapkan sebagai pengantar untuk mendiskusikan sebuah perspektif teoritis yang umumnya menjadi kerangka pikir para sarjana – baik itu dalam disiplin ilmu consumer research, maupun juga di disiplin-disiplin ilmu lain yang berdekatan – dalam meneliti tentang ketiga aspek identitas yang disinggung di atas. Adams (2006) menyebut bahwa dalam percakapan kontemporer tentang identitas, terdapat dua kerangka berpikir dominan yakni self–reflexivity dan habitus. Perspektif yang pertama dipelopori oleh Anthony Giddens (1991) dan Ulrich Beck (1992) – dua sosiolog ternama yang mengulas kaitan identitas dan modernisasi. Habitus, sementara itu, adalah salah satu konsep yang dicetuskan oleh Pierre Bourdieu, sosiolog Perancis, bersama dengan dua konsep penting lainnya yakni field dan capital. Sosiolog feminis asal Inggris, Beverley Skeggs (2004a) menyajikan rangkuman yang lebih lengkap tentang kerangka berpikir mengenai identitas dalam teori sosial kontemporer, antara lain identitas sebagai aesthetic-self (diilhami oleh gagasan Foucault (1979) tentang technology of the self), identitas sebagai prosthetic-self (dipelopori oleh sosiolog Celia Lury (1998)), identitas sebagai reflexive-self (sebagaimana digagas oleh Giddens dan Beck), identitas sebagai possessed individuality (dikemukakan oleh Kroker (1992), dan habitus. Makalah ini tidak bermaksud meringkas setiap kerangka pikir di atas, namun akan lebih dipumpun pada kerangka pikir yang ditawarkan oleh Bourdieu untuk memahami identitas, yakni dari Habitus.
Apa itu Habitus?
Bourdieu menyebut Habitus sebagai “a system of lasting transposable dispositions which, integrating past experiences, functions at every moment as a matrix of perceptions, appreciations, and actions” (Bourdieu 1977: 82-83). Cukup rumit untuk mengartikan definisi ini secara gamblang, namun sekurang-kurangnya artinya menunjuk pada kecenderungan-kecenderungan yang telah menubuh (embodied) pada diri seseorang, dan karenanya menatakelolai cara orang itu memandang, menghargai, merasa, memaknai, dan menindak pelbagai realita sosial yang Ia hadapi dalam lingkungan sosial yang Ia jelajahi dan tinggali. Singkatnya, Habitus menjelma sebagai ways of being atau ways of living seseorang dan nyata dalam interaksinya di ruang sosial tertentu. Habitus terbentuk dari struktur sosio-kultural yang sifatnya berada di luar diri individu, dan kadang tidak Ia sadari sepenuhnya, yakni diskursus, norma-norma, nilai-nilai, ideologi, praktik-praktik sosial, kelas sosial, dan lain-lain yang menyekitari hidup individu tersebut (Skeggs 2004a). Pertemuan antara individu dengan struktur di luar dirinya inilah yang kemudian menghasilkan pengalaman hidup (lived experience), yang kemudian ‘meninggalkan jejak’ atau membatin pada diri individu tersebut sebagai identitasnya (Crossley 2001). Struktur adalah bagian dari sejarah kolektif suatu masyarakat di mana seorang individu berada, yang juga memengaruhi aturan main (rules of the game) dalam setiap ruang sosial yang lebih mikro. Habitus, dengan demikian, adalah “product of the work of inculcation and appropriation necessary in order for those products of collective history, the objective structures (language, economy, etc), to succeed in reproducing themselves more or less completely, in the form of durable dispositions” (Bourdieu 1977: 85). Habitus adalah kecenderungan-kecenderungan batiniah dan jasmaniah seseorang yang darinya suatu struktur sosial budaya mereproduksi dirinya sendiri.
Dengan demikian, Habitus perlu dipahami sebagai sistem yang membentuk sekaligus produk atau hasil bentukan (Skeggs 2004a). Cara hidup atau tindakan (produk) seseorang mencerminkan setiap diskursus dan sistem sosial budaya di mana orang tersebut berada (sistem).
Berangkat dari pemahaman ini, ada kritik bahwa Habitus sifatnya sangat deterministik (Adams 2006), seolah-olah seorang individu tidak dapat bertindak – entah didorong oleh imajinasi, maupun kekuatan lain di luar lingkungan sosialnya – secara berbeda dari latar belakang sosial-budayanya[2].
Habitus mengimplikasikan bahwa perilaku individu didikte oleh struktur sosial di mana individu itu berada. Beberapa penelitian yang saya temui dalam lingkup keilmuan saya membenarkan bahwa latar belakang sosial budaya seseorang itu bersifat persisten (Ustuner dan Holt 2007; Allen 2002), namun bukan berarti tidak bisa diterobos (Castilhos dan Fonseca 2016), jika seseorang memiliki akses terhadap sumber daya kultural dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melampaui struktur tersebut (Skeggs 2004b). Pemahaman tentang habitus sebagai sistem sekaligus produk, dan juga kaitannya dengan akses terhadap sumber daya kultural inilah yang membawa pemahaman alternatif mengenai identitas, yang akan saya bahas selanjutnya.
Identitas, habitus, dan akses terhadap sumber daya kultural
Skeggs (2008: 11) berargumen bahwa kita perlu memahami perbedaan antara “mendiami sebuah posisi identitas, membuat identifikasi, diposisikan oleh identitas, atau mengalami pribadi (personhood) tertentu seolah-olah itu adalah identitas.[3]” Setiap posisi identitas memiliki keterkaitan dengan sistem sosial budaya. Identitas adalah produk sekaligus representasi dari sistem. Ketika seseorang dilahirkan dan tumbuh sebagai laki-laki atau perempuan, maka serta-merta Ia telah mendiami suatu posisi identitas, dan langsung pula dituntut untuk mempertunjukkan, atau memerankan (performing) identitas itu. Kemampuan orang tersebut dalam mempertunjukkan identitas sesuai dengan norma-norma kultural yang berlaku akan mempengaruhi diterima atau tidaknya orang tersebut dalam masyarakat yang Ia tinggali. Demikian pula dengan identitas-identitas sosial seperti suami, istri, presiden, perdana menteri, peneliti, mahasiswa doktoral, dan lain-lain. Dalam hal ini, identitas dapat dimaknai sebagai tanda kultural yang melekat atau dilekatkan pada diri seseorang, dan berhubungan pula dengan peran sosialnya.
Ada kala sebuah tanda atau identitas itu terberi (given) begitu saja (sebagai contoh, lahir sebagai laki-laki, atau lahir sebagai anak Sultan Yogyakarta). Namun, terkadang pula, tanda itu harus diraih, diperjuangkan, atau dibayangkan terlebih dahulu (seperti, menjadi PhD). Sama hal pula, seseorang bisa membuat identifikasi dengan suatu identitas yang berada di luar lingkup sosio-kultural di mana Ia lahir, selayaknya seorang anak Indonesia menyebut diri sebagai penggemar grup K-Pop BTS, atau penggemar sejati Real Madrid. Dalam kasus ini, seseorang perlu mengakses berbagai sumber daya yang tepat untuk menunjukkan bahwa Ia layak menyandang identitas yang dibayangkannya, atau agar Ia dapat sepenuhnya diidentifikasi seperti yang diinginkannya.

Sumber: Identitas penggemar bola (pixels.com)
Terkadang pula, seseorang bisa diposisikan oleh identitas, seperti seorang anak sulung yang menjadi yatim karena ayahnya meninggal, atau seorang ibu yang divonis menderita kanker oleh dokter. Dalam kasus ini, identitas tidak dipilih secara bebas, sebagaimana dalam perihal membuat identifikasi. Tanpa keinginan mereka sendiri, individu-individu dapat diposisikan oleh identitas, dan selanjutnya harus menyesuaikan tindakan atau perilaku mereka sesuai dengan identitas yang dilekatkan pada diri mereka itu. Hal ini pun amat terkait dengan stigma, sebagaimana yang kita temukan pada perlakuan diskriminatif terhadap keturunan para korban tragedi politik masa lalu.
Perlu juga dibedakan juga antara pribadi dan identitas. Yang pertama sifatnya lebih temporer dan situasional, mudah berubah dalam lintasan ruang dan waktu, sedangkan identitas sifatnya terkait keseluruhan pemahaman diri seorang dalam perjalanan hidupnya. Ketika seseorang menyatakan bahwa “saya pernah dikenal sebagai orang yang A tapi sekarang saya sudah lebih B” maka A dan B menunjuk pada pribadi, bukan identitas, orang tersebut dalam dua titik perjalanan hidup yang berbeda. Identitas lebih menunjuk pada kumpulan dari pribadi-pribadi, a bundle of the selves, yang pernah dialami seorang individu semasa Ia hidup (Cherrier dan Murray 2007).
Keempat proses di atas – mendiami identitas, membuat identifikasi, diposisikan oleh identitas, dan mengalami pribadi seolah-olah itu adalah identitas – dapat terjadi secara bersamaan dan saling terhubung dalam satu titik perjalanan hidup seseorang. Dengan menggunakan Habitus sebagai kerangka pikir, maka setidaknya ada dua hal yang perlu kita catat. Pertama, setiap identitas yang melekat atau dilekatkan pada diri seseorang adalah produk dari struktur sosial budaya yang lebih luas, yang serta merta menuntut orang tersebut untuk bertindak seturut diskursus dan norma terkait identitas tersebut. Skeggs (2004b) mengintroduksi dua konsep penting yang membantu kita memahami implikasi-implikasi dari mempertunjukkan identitas: mobility and fixity. Bagi Skeggs, kemampuan seseorang dalam mempertunjukkan identitas sesuai norma yang berlaku dapat disamaartikan dengan bermain menurut aturan main dalam suatu ruang sosial. Ketika seseorang mampu bermain menurut aturan main, Ia dapat bergerak secara leluasa dalam ruang sosial yang Ia diami, bahkan berpindah ke ruang sosial lain yang memiliki aturan main yang mirip. Orang tersebut menjadi socially mobile. Sebaliknya, ketidakmampuan untuk bermain menurut aturan main akan membuat seseorang sulit bergerak, hanya terpaku, fixed, pada satu ruang sosial yang sesuai dengan kemampuannya.
Beberapa contoh tentang play the game atau mempertunjukkan identitas bisa dikemukakan di sini. DeVault (1991) dalam bukunya tentang motherhood menyebut sifat-sifat seperti penuh kepedulian, kasih-sayang, dan pengorbanan diri adalah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang “ibu yang baik.” Diskursus ini menempatkan setiap ibu atau perempuan yang dianggap tidak mampu menunjukkan sifat-sifat tersebut sebagai yang gagal, atau tidak mampu menjadi ibu. Mempertunjukkan identitas sebagai ibu yang baik memiliki konsekuensi ekonomis dan kultural, karena di masyarakat modern kontemporer, setiap tanda kasih-sayang dan pengorbanan makin dimediasi oleh konsumsi dan interaksi di ruang-ruang komersil (Hamilton 2009). Akibatnya, bagi sebagian mereka yang tidak memiliki sumber-daya ekonomi dan kultural untuk membeli dan memanfaatkan ragam produk dan jasa di ranah komersil, guna mendemonstrasikan kasih sayang mereka terhadap anak dan keluarga, kemudian merasa gagal, kurang, atau tidak mampu (Harman dan Chapellini 2015). Hal ini ikut diperparah oleh iklim neoliberalisme pasar yang mengagungkan kompetisi antar individu. Di sini kita bisa melihat bahwa identitas (ibu yang baik) itu amat dipengaruhi oleh diskursus sosial-budaya dan kemampuan mempertunjukkannya juga ditentukan akses terhadap sumber daya kultural.
Di konteks Indonesia, hal yang sama terjadi pula dalam konteks anak muda. Menurut Beta (2020), di masa pemerintahan Presiden Jokowi, ada semacam gagasan bahwa anak muda ideal adalah mereka yang entrepreneurial, mampu merintis perusahan start up yang sukses, mengenyam pendidikan bertaraf internasional, tamat dari kampus-kampus ternama dunia, dan aktif secara sosial politik. Gagasan ini termanifestasi dalam pemilihan staf khusus milenial di tahun 2020 lalu. Konstruksi tentang anak muda ideal ini, oleh Beta (2020), dianggap buta kesenjangan, karena sebagian besar anak muda Indonesia hidup dalam ketidakpastian ekonomi, sulit mengakses pendidikan tinggi dan masuk dalam lapangan kerja sebagai sumber daya yang memungkinkan mobilitas ke atas (upward mobility) sebagaimana diidealkan oleh pemerintah.
Hal kedua yang perlu dicatat adalah bahwa akses terhadap sumber daya kultural amat menentukan bagaimana seseorang menjalani, menghidupi, mengembangkan, melawan, atau mentransformasi identitas yang melekat/dilekatkan padanya. Sumber daya kultural yang dimaksud dapat berupa objek, pengetahuan, dan teknik untuk memerankan, memainkan, atau mempertunjukkan identitas tertentu. Akses tidak hanya berhubungan dengan pertanyaan apa (the what), tetapi juga bagaimana. Seseorang bisa pergi ke galeri, museum, atau mengikuti kursus musik, namun bisa saja tidak menikmati sajian atau karya-karya seni di sana dan menggunakannya dalam bersosialisasi dengan orang lain. Dalam hal ini, seseorang bisa memiliki akses terhadap sumber daya kultural, namun kekurangan pengetahuan dan teknik untuk menggali, mengolah, dan menggunakan pengetahuan seni yang Ia dapatkan di sana.
Penelitian dari Ustuner dan Holt (2007) tentang praktik konsumsi para perempuan migran dari kelas pekerja, yang tinggal di daerah pinggiran kota Ankara, Turki, memberi contoh gamblang tentang bagaimana akses terhadap objek, pengetahuan, dan teknik dalam memainkan sebuah identitas memiliki dampak signifikan dalam hidup seseorang. Kedua peneliti ini melaporkan bahwa setelah para perempuan tersebut bermigrasi dari desa ke kota, mereka terpapar dengan Batici, sebuah konstruksi sosial tentang perempuan modern Turki yang padanya melekat gaya hidup dan ekspektasi tertentu (misalnya, cara berpakaian, cara menghabiskan waktu luang, cara membelanjakan dan mengonsumsi, berkarir, mengurus keluarga dan rumah tangga, dan lain-lain). Konstruksi ini mereka temukan berbeda dengan nilai-nilai dan cara hidup di tempat asal mereka. Berada dalam ruang sosial ala kota modern, para perempuan ini dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan konstruksi ideal tentang perempuan tersebut. Ustuner dan Holt (2007) menemukan bahwa para perempuan ini menggunakan dua spektrum strategi untuk menyesuaikan diri mereka: 1) menolak gaya hidup Batici, dan mempraktikkan kembali cara hidup mereka di desa seturut dengan akses dan pengetahuan kultural yang telah menubuh pada diri mereka; 2) mencoba meninggalkan cara hidup mereka yang lama, dan berasimilasi dengan kehidupan perempuan modern ala Batici, di tengah keterbatasan objek, pengetahuan, dan teknik untuk memainkan identitas perempuan modern itu. Ustuner dan Holt menemukan bahwa ada beberapa perempuan migran yang sukses dalam menempuh kedua strategi di atas, namun ada pula yang terjebak di tengah-tengah kedua spektrum strategi tersebut. Mereka merasa terasing ketika memerankan cara hidup desa di kota, namun tidak memiliki sumber daya kultural yang cukup untuk memenuhi tuntutan peran perempuan modern. Kondisi terjebak ini membuat para perempuan migran mengalami apa yang disebut oleh Ustuner dan Holt (2007) sebagai shattered identity.
Catatan penutup
Diperlukan kehati-hatian dalam melihat beragam diskursus dibalik sebuah identitas, baik itu identitas individual maupun sosial, dan posisi seseorang dalam ruang sosial dalam meraih sumber daya-sumber daya penting untuk memerankan identitasnya (Skeggs 2011). Tulisan sederhana ini kiranya dapat menjadi pengantar yang baik untuk mendiskusikan identitas sebagai salah satu pokok yang amat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Habitus sebagai sebuah kerangka pikir dari Bourdieu dapat membantu kita dalam memahami kompleksitas identitas manusia modern dan memungkinkan kita untuk memahami ketimpangan sosial di masyarakat.
Reference:
[1] A set of features that comprise a given person’s character, which is thought to be relatively stable and scaffolded by genetically determined traits (Schau 2019: 38).
[2] Tuduhan inilah yang sekiranya akan membawa kita pada perspektif reflexivity tentang identitas.
[3] Inhabiting an identity position, making an identification, being positioned by identity, and experiencing personhood as if it is an identity (Skeggs 2008: 11).
Adams, M., (2006) Hybridizing reflexivity and habitus: Towards an understanding of contemporary identity? Sociology, Volume 40 (3):511-528.
Allen, Douglas E. (2002), Toward a Theory of Consumer Choice as Sociohistorically Shaped Practical Experience: The FitsLike-a-Glove (FLAG) Framework, Journal of Consumer Research, 28 (4), 515–32.
Beck, U. (1992) Risk Society. London: Sage.
Beta, Annisa R., (2020) Politics of youth survival in times of crisis, Inter-Asia Cultural Studies, 21:4, 484-494, DOI: 10.1080/14649373.2020.1832297.
Bourdieu, P., (1977) Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Polity Press.
Castilhos, Rodrigo B., Fonseca, Marcelo J., (2016), Pursuing upward transformation: the construction of progressing self among dominated consumers, Journal of Business Research, 69, 6-17.
Cherrier, H., & Murray, Jeff B., (2007) Reflexive Dispossession and the Self: Constructing a Processual Theory of Identity, Consumption Markets & Culture, 10:1, 1-29, DOI: 10.1080/10253860601116452.
Crossley, N. (2001) ‘The Phenomenological Habitus and its Construction’ Theory and Society 30: 81–120.
DeVault, M., (1991) Feeding the Family. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Foucault, M. (1979) The History of Sexuality, Volume One. Harmondsworth: Penguin.
Giddens, A. (1991) Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity.
Hamilton, K., (2009) Low-income families: Experiences and responses to consumer exclusion, International Journal of Sociology and Social Policy, 29, 543–557. https://doi.org/10.1108/01443330910986315.
Harman, V., and Cappellini, B., (2015) Mothers on display: lunchboxes, social class, and moral accountability, Sociology, Vol 49 (4), 764-781.
Kroker, A. (1992) The Possessed Individual: Technology and the French Postmodern. New York: St Martin’s Press.
Lury, C. (1998) Prosthetic Culture: Photography, Memory and Identity. London: Routledge.
Schau, Hope J., (2018) Identity Projects and the Marketplace, in Arnould, Eric J., and Thompson, Craig J., (eds), Consumer Culture Theory, London: SAGE.
Skeggs, B. (2004a). Exchange, Value and Affect: Bourdieu and ‘The Self.’ The Sociological Review, 52(2_suppl), 75–95. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2005.00525.x.
Skeggs, B., (2004b) Class, self, and culture, London: Routledge.
Skeggs, B., (2008) The Problem of Identity, in Lin, A. (ed) Problematizing Identity: Everyday Struggles in Language, Culture, and Education, New York: Taylor & Francis.
Skeggs, B., (2011) Imagining personhood differently: person value and autonomist working-class value practices, The Sociological Review, 59:3.
Üstüner, T., Holt, Douglas B., (2007), Dominated Consumer Acculturation: The Social Construction of Poor Migrant Women’s Consumer Identity Projects in a Turkish Squatter, Journal of Consumer Research, Volume 34, Issue 1, June 2007, Pages 41–56, https://doi.org/10.1086/513045.
*) Artikel ini adalah aset pengetahuan organisasi Doctrine UK dengan nomor registrasi 2022-10-6-Articles.